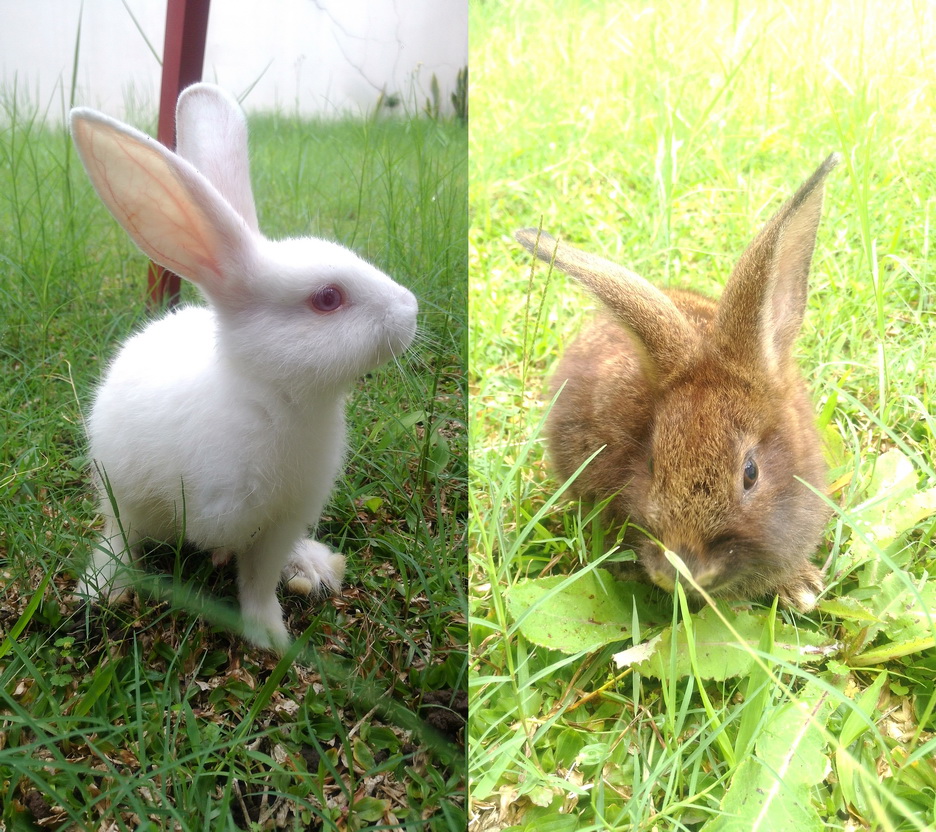Tek Sua, Acan… sampai jumpa lagi. Nanti aku belajar dari kalian lagi.
Wisuda magister bulan Mei lalu adalah salah satu momen bahagia diri di tahun ini, lalu Tek Sua, tante, pulang ke Pelukan Tuhan beberapa hari sebelumnya. Juni penuh dengan hal-hal membahagiakan. Awal Juli, Acan, paman, juga kembali pada-Nya.
Kesedihan benar-benar tak pernah pergi ya, semesta, dia hanya terus bertukar wajah.
Mereka berdua benar-benar menjadi pilar dari hendak menjadi orang seperti apa saya ini. Saya belajar tentang keteguhan dalam menghadapi nasib benar-benar dari orang terdekat.
Tek Sua adalah adik kedua Ayah. Mereka 4 bersaudara, paman termuda saya dari Ayah mengalami tuna grahita, tapi tak pernah kekurangan kasih sayang akibat kekurangannya. Beliau berpulang beberapa tahun lalu, membawa setengah semangat hidup Nenek.
Semua anggota keluarga dididik keras oleh keadaan. Ekonomi keluarga menjadikan mereka tak pernah punya keleluasaan memilih. Ayah hanya sampai kelas 3 SD, setelah banyak waktunya harus habis untuk berjualan gorengan keliling kampung. Atau kadang membantu memanen kelapa. Adik-adiknya juga tak lebih baik. Hanya Tek Sua barangkali yang sedikit lebih baik, sampai SMK—kata Ayah, perempuan harus lebih tinggi sekolahnya. Tek Sua satu-satunya anak perempuan di keluarga itu.
Tek Sua membantu Nenek mengurusi sawah warisan yang lumayan besar. Hasilnya dipakai untuk hidup sepanjang tahun. Cukup. Dan pada suatu kondisi yang lebih baik, Tek Sua membuka satu warung kopi di depan rumah Nenek. Kadai, kalau orang Minang menyebut sebuah warung. Kadai dulunya merupakan bagian dari kebudayaan Minang, tempat orang (umumnya laki-laki) berkumpul sepulang sembahyang dari surau selepas isya. Di tempat ini mereka membincangkan apa saja, mulai dari obrolan ringan sampai berdebat. Pulang ke rumah baru selepas tengah malam, kadang-kadang. Begitu terus setiap hari. Sebelum televisi masuk ke tiap rumah, dan kini smartphone masuk sampai ke kamar.
Tek Sua menikah dengan laki-laki dari kampung sebelah. Kondisinya tak lebih baik. Waktu akhirnya menunjukkan bahwa harus Tek Sua lah yang menjadi tulang punggung keluarganya, sementara suami bekerja serabutan lebih banyak tak menghasilkan.
Tapi tak pernah sekalipun saya dengar dia mengeluh. Dia tetap riang tiap bertemu saya, menjamu saya bak raja dan seolah dia memiliki begitu banyak hal di dunia—kekayaan mungkin lebih ke state of mind dibanding jumlah tabungan di rekening.
Anak pertama kemudian lahir, lalu kedua, dan ketiga. Laki-laki semua. Warung tetap berjalan seperti biasa dan bertahan. Pernah pada suatu kali saya melihat seorang pelanggan mengambil barang ini dan itu… pelanggan tanya harganya, Tek Sua sebutkan. Saya tahu bahwa Tek Sua mengambil laba kelewat sedikit dalam sudut pandang saya. Pelanggan mengambil barangnya lalu meminta ditambahkan dalam catatan daftar hutangnya. Ya Tuhan… laba segini dan dibayar entah kapan.
Saya tanya. “Tek Sua tak masalah dihutangi begitu? Kan labanya juga tak banyak…” sembari protes.
“Tidak masalah. Memang begitu kalau di sini…”
Kelapangan yang dia miliki inilah yang kemudian membentuk bagaimana sikap orang terhadap Tek Sua. Seumur hidup saya ini, belum pernah saya melihat begitu banyaknya orang mengantar jenazah seperti di pemakanan Tantemu ini, kata Ayah saat saya bertanya perihal hari penuh sunyi itu.
Acan adalah pilar teguh yang lain. Beliau praktis menjadi kakak tertua setelah anak pertama di keluarga Ibu meninggal muda. Ini yang kemudian saya jadikan panutan tentang bagaimana cara menjadi anak pertama yang baik.
Ketika adik-adiknya ribut tentang pembagian tanah yang ditinggalkan Nenek-Kakek, dia tidak ikut-ikutan. Sama sekali tidak mengambil sepeser pun dari bagian atau bahkan keuntungan dari pembagian itu—maklum beberapa tanah kemudian disewakan kepada orang lain. Dia memilih menjauh, membeli satu tanah kecil di kampung orang, agak berjarak dari jalan raya, menujunya dulu hanya bisa naik sepeda motor, kini sudah sebesar jalan 1 mobil. Tanah ini bertetangga dengan pekuburan, hal yang tentu dihindari oleh siapa saja yang hendak memilih tempat bermukim, hingga kini. Tapi karena keterbatasan ekonomi jua lah, hanya tanah ini yang mampu dia dan istri beli. Rumahpun dibangun dari amat sangat sederhana dulu. Dari kayu, lantainya tanah. Lalu tambah beton di sana sini. Baru belakangan saja rumahnya rampung. Kecil, sederhana, cukup dan indah. Gabungan beton dan kayu. Komposisinya baik, karena memang dia adalah seorang tukang.
Dia memilih menjadi tukang. Profesi yang cukup keras tapi dia jalani dengan ringan saja. Pada suatu kepulangan, saya bertemu dengannya, kulitnya sedang sangat legam terbakar matahari. Tapi senyum ramah tak pernah hilang dari wajahnya. Keceriaan ini yang menimbulkan luka pada diri saya sendiri—dia adalah paman yang tak mungkin saya biarkan menderita segitunya oleh nasib.
Sudah umum di Minangkabau untuk mengedepankan pendidikan anak di atas kepentingan apapun di dunia ini. Apapun mesti dilakukan demi anak tetap bisa bersekolah. Begitu juga di Ayah dan Ibu, tapi mereka tetap butuh penopang untuk keputusan akhir menyekolahkanku ke Bandung. 40 jam jaraknya dari rumah. Hampir 2 hari 2 malam di masa di mana pesawat hanya untuk orang yang benar-benar kaya. Bukan sebuah keputusan mudah. Ayah dan Ibu kemudian ditopang oleh Kakek dan Acan.
Acanlah salah satu orang yang ngotot saya harus disekolahkan ke Jawa. Dia besarkan hati Ibu bahwa rezeki bisa dicari dan kesempatan mungkin benar-benar hanya datang sekali. Sebagai perbandingan, saat itu, hanya ada 1 orang anak di kota kecil itu yang mampu tembus ke ITB tiap tahunnya. Saya masih ingat raut wajah bangga Acan saat membaca namaku tertulis di bagian paling atas daftar anak didik sebuah bimbingan belajar yang tembus kuliah di ITB. Ini keponakanku, katanya.
Setelah saya kuliah di Bandung, kami bertemu praktis hanya sekali dalam setahun. Bila saya pulang hari ini, besoknya saya pasti langsung ke rumah kecilnya. Dalam bertahun-tahun lamanya, keadaan tetap tak membaik. Pernah suatu kali saya datang di sebuah sore dan itu adalah jam-jam anaknya mandi. Acan punya 3 orang anak, 2 perempuan dan laki di bungsu. Saya lihat handuk mereka. Compang camping! Benar-benar compang camping! Sementara anak semakin beranjak gadis.
Tapi tetap tak ada keluhan. Yang ada benar-benar hanya rasa syukur yang tulus. Tak dibuat-buat, kau tentu tahu bedanya. Dan sekali lagi, ini membekaskan luka di diri saya sendiri. Di luar saya yang mampu membuatnya bangga, saya juga harus membantu agar nasib tak terlalu keras pada mereka. Dan terbukti bahwa saya belum segitunya berguna.
Acan kemarin sore dibawa ke rumah sakit karena perutnya semakin sakit. Penyakit liver, kata dokter. Malamnya dia berpulang.
Dua orang ini kini telah kembali. Adik Ayah dan Kakak Ibu. Tentu separuh jiwa mereka kehilangan. Kalau sudah begini, pertahanan saya tentu jebol juga.
Kemarin Ibu mengabari, telepon kami berjalan sangat singkat. Saya sedang dilanda kosong, apalagi Ibu. Pagi tadi saya telepon kembali Rumah, Ibu menangis, saya diam saja. Tak mau menambah sedihnya.
Di dua kehilangan ini, saya tak bisa berbuat banyak. Saya tak bisa melihat mereka untuk terakhir kalinya. Pesawat tercepat hanya mampu membuat saya sampai sore atau malam di rumah.
“Tak apa, Nak…” kata Ibu.
Tapi ini getarnya tak kunjung berhenti… saya tulis ini dengan begitu banyak jeda. Jari saya bergetar. Pertahanan saya runtuh.